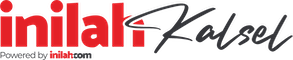Gamis Pernah Jadi Simbol Perlawanan terhadap Belanda

Pakaian haji atau gamis menjadi salah satu identitas Muslim di Nusantara. Kepopuleran gamis bahkan hadir sejak zaman penjajahan Belanda. Gamis saat itu jadi simbol ‘Kenusantaraan’ dan perlawan terhadap penjajah.
Gelora perlawanan itu dibuktikan dengan banyaknya pemuka agama Islam –utamanya yang sudah berhaji– memimpin perlawanan di berbagai penjuru Nusantara. Belanda panik. Bahkan siapapun yang memakai gamis dicurigai akan melawan Belanda.
Awalnya, ibadah haji bagi kaum bumiputra adalah aktivitas normal di Hindia-Belanda. Keinginan mendekatkan diri kepada Tuhan itu bahkan didukung oleh Belanda. Pun karena yang berangkat naik haji hanya kalangan terbatas.
Biaya untuk menunaikan rukun Islam kelima terlampau besar. Namun, semakin tahun jumlah orang yang mendedikasikan uang dari pekerjaannya untuk naik haji semakin meningkat.
Buahnya, hal yang tak disangka-sangka terjadi. Muncul berbagai macam pemberontakan di sepanjang paruh abad ke-19. Kebetulan banyak di antaranya dipelopori oleh pemuka agama Islam, termasuk para haji.
Gelagat itu lalu dicium pertama kali oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811). Pemerintah kolonial Belanda yang mulai panik lalu membatasi ibadah haji. Belanda kemudian menganggap ibadah haji bukan melulu urusan keagamaan, tapi menjadi sebentuk ancaman.
“Beberapa peraturan dibuat pemerintah Hindia-Belanda di Batavia dalam urusan agama Islam: masalah haji, bahwa pelaksanaan ibadah haji di abad ke-19 dapat disebut sebagai ‘haji phobi.’ Dalam sejarah politik haji di Indonesia, Daendels merupakan Gubernur Jenderal Belanda pertama yang memerintahkan jemaah haji harus menggunakan paspor jalan, dengan alasan keamanan dan ketertiban,” ungkap Abdullah Idi dalam buku Politik Etnisitas Hindia-Belanda (2019).
Peraturan itu diterapkan oleh Daendels karena ragam kekhawatiran. Pemerintah kolonial Belanda baru menyadari kedudukan haji dalam masyarakat Hindia begitu dihormati. Pengikutnya pun banyak.
Apalagi, pengalaman di masa lalu memperlihatkan banyak pemberontakan yang dipelopori para haji. Upaya perlawan itu muncul tak lain karena para jamaah haji berjumpa dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia.
Imbasnya, wawasan jemaah haji menjadi lebih luas termasuk banyak dipengaruhi oleh semangat Islamisme. Kondisi yang sama turut direkam oleh Letnan Gubernur Hindia-Belanda (1811-1816), Thomas Stamford Raffles, saat berkuasa.
Raffles menyadari bahwa pengaruh para haji dalam mengobarkan pemberontakan sangat besar. Seorang haji dapat menjelma menjadi tokoh penting di suatu kawasan.
Mereka dituakan, juga dianggap sosok pemimpin ideal. Tak jarang pula para haji disebut sebagai juru selamat dari kemelaratan dan penindasan ala penjajah.
“Setiap orang Arab dari Mekkah, seperti halnya orang Jawa yang kembali dari perjalanan sucinya, berpendapat bahwa orang jawa mempunyai karakter sebagai seorang penyelamat, dan sebagai besar mempunyai kecenderungan yang mudah dalam memahami sesuatu, bahkan mereka terkadang mempunyai kemampuan supranatural. Berdasarkan tanggapan tersebut, tidak sulit membangkitkan mereka untuk mengadakan sesuatu pemberontakan, dan mereka menjadi alat berbahaya di tangan penguasa daerah dalam melawan Belanda,” tulis Raffles dalam mahakaryanya The History of Java (1817).
“Para ulama agama Islam terlibat dalam berbagai perlawanan rakyat. Beberapa di antara mereka merupakan keturunan arab dengan wanita pribumi, yang pergi jauh dari wilayahnya di kepulauan Timur, dan umumnya hal itu karena adanya intrik dan kekerasan di antara mereka. Kepala suku telah diperalat untuk menyerang atau membantai orang-orang Eropa sebagai orang-orang yang tidak percaya dan penyusup,” tambahnya.
Gamis Simbol ‘Kenusantaraan’ dan Perlawanan
Dalam masa itu pemerintah kolonial Belanda menelurkan peraturan baru tentang haji pada 1859. Peraturan tersebut termuat dalam Staatsblad tanggal 6 Juli 1859 No. 42 memuat tiga ketentuan utama tentang ibadah haji.
Pertama, paspor jalan tetap diwajibkan dan gratis. Kedua, calon haji harus membuktikan kepada kepala daerah bahwa ia memiliki uang yang cukup untuk perjalanannya pulang dan pergi, serta untuk biaya keluarga yang ditinggalkan.
Ketiga, setelah kembali dari Mekkah para jemaah haji diuji oleh bupati/kepala daerah atau petugas yang ditunjuk. Setelahnya, mereka yang lulus saja yang diperkanankan memakai gelar dan pakaian haji (gamis).
Alhasil, gamis langgeng menjadi budaya berpakaian baru di kalangan kaum bumiputra. Tren gamis bagi pemuka agama juga jadi bagian dari simbol perlawanan terhadap penjajah.
Lantaran sejak dijajah Belanda, kaum bumiputra sering kali dilarang berpenampilan ala Eropa. Kala gamis masuk, maka budaya pakaian asal Arab itu makin kesohor di penjuru negeri. Semua itu berkat para pemuka agama yang naik haji dan menjadikan gamis sebagai pakaian wajibnya di Nusantara.
“Salah satu kebiasaan jamaah haji Hindia Belanda adalah mengenakan pakaian haji (gamis) setelah melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, dana untuk pakaian haji itu telah disiapkan tersendiri sebagaimana terlihat pada setiap perhitungan biaya perjalanan haji. Pada 1931, misalnya, untuk pakaian haji disiapkan dana sekitar 75 gulden dari 823 gulden jumlah biaya yang diperlukan oleh seorang jemaah haji. Pada waktu itu, pakaian haji dibuat dan dibeli di Mekkah,” ujar M. Shaleh Putuhena dalam buku Historiografi Haji Indonesia (2007).
Tradisi berpakaian gamis yang dibawa para haji cepat menyebar. Selain pemuka agama, gamis juga sering digunakan oleh pejabat-pejabat bumiputra –seperti bupati– dalam hari-hari tertentu. Bupati Bandung (1920-1931), Raden Aria Adipati Wiranatakoesoema V, misalnya.
Dalam setiap kesempatan berjumpa dengan rakyatnya, Bupati Bandung tersebut sering kali mengenakan gamis. Setelahnya, pemerintah kolonial Belanda menganggap popularitas sang bupati yang berpenampilan Islami dapat membayakan Hindia-Belanda.
“Menurut pengamatan puterinya, yang menyertai Bupati Bandung ini, dalam kunjungan-kunjungan ke pedesaan, ayahnya tampak begitu popular karena ia mau berbicara dan mendengarkan rakyatnya. Timbulnya sikap antipati ini karena popularitas ayahnya di mata rakyat bisa saja dipandang membahayakan Pemerintah Hindia-Belanda. Bagaimanapun, perilaku Bupati Bandung ini telah menampilkan diri sebagai pemimpin pribumi yang taat beragama,” tutup Ading Kusdiana dalam buku Sejarah Pesantren (2014).